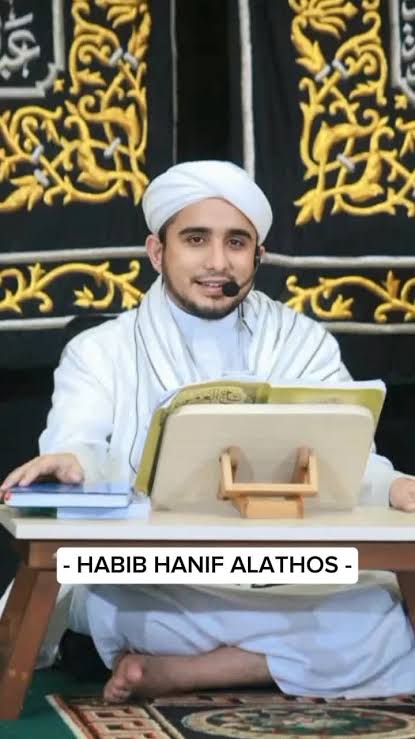✍️ Ustadz Fahri Nusantara ( UFN )
Panggung kehidupan beragama di Indonesia kadang menghadirkan drama tak terduga. Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan dua peristiwa yang terasa janggal. Pertama, sebuah video menampilkan seorang pendeta memimpin doa dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, sebuah momen sakral yang seharusnya menjadi ranah ulama dan umat Islam. Kedua, dalam acara peresmian pastori—rumah dinas resmi pendeta dalam tradisi Protestan—justru yang hadir memberi sambutan adalah seorang ustadz.
Pastori sendiri adalah istilah serapan dari bahasa Belanda pastorie, yang berarti rumah pendeta. Fungsinya mirip dengan rumah dinas pejabat negara, namun secara khusus diperuntukkan bagi gembala jemaat. Dalam tradisi Kristen Protestan, pastori bukan sekadar tempat tinggal, melainkan simbol pelayanan rohani yang melekat pada otoritas pendeta. Karena itu, peresmian pastori oleh seorang ustadz jelas menimbulkan tanda tanya besar: mengapa urusan yang begitu kental dengan identitas Kristen justru dipimpin tokoh dari luar tradisi tersebut?
Hal yang sama terasa aneh ketika seorang pendeta berdiri di acara Maulid Nabi. Maulid bukan sekadar acara seremonial, melainkan ekspresi cinta dan penghormatan umat Islam kepada Rasulullah SAW. Kehadiran pendeta sebagai pemimpin doa di situ bukan hanya janggal, tetapi juga mengaburkan batas identitas agama.
Dua peristiwa ini menghadirkan ironi. Alih-alih menegaskan toleransi, yang muncul justru kebingungan. Toleransi bukanlah menukar peran suci masing-masing agama. Toleransi sejati justru menghormati batas-batas sakral itu: ulama menjaga ruang Islam, pendeta menjaga ruang Kristen. Ketika peran tertukar, yang lahir bukan harmoni, melainkan paradoks—keterbalikan yang menimbulkan tanya.
Fenomena ini menjadi cermin: sampai di mana kita memahami makna toleransi? Apakah saling menghormati, atau justru melebur hingga kehilangan jati diri?