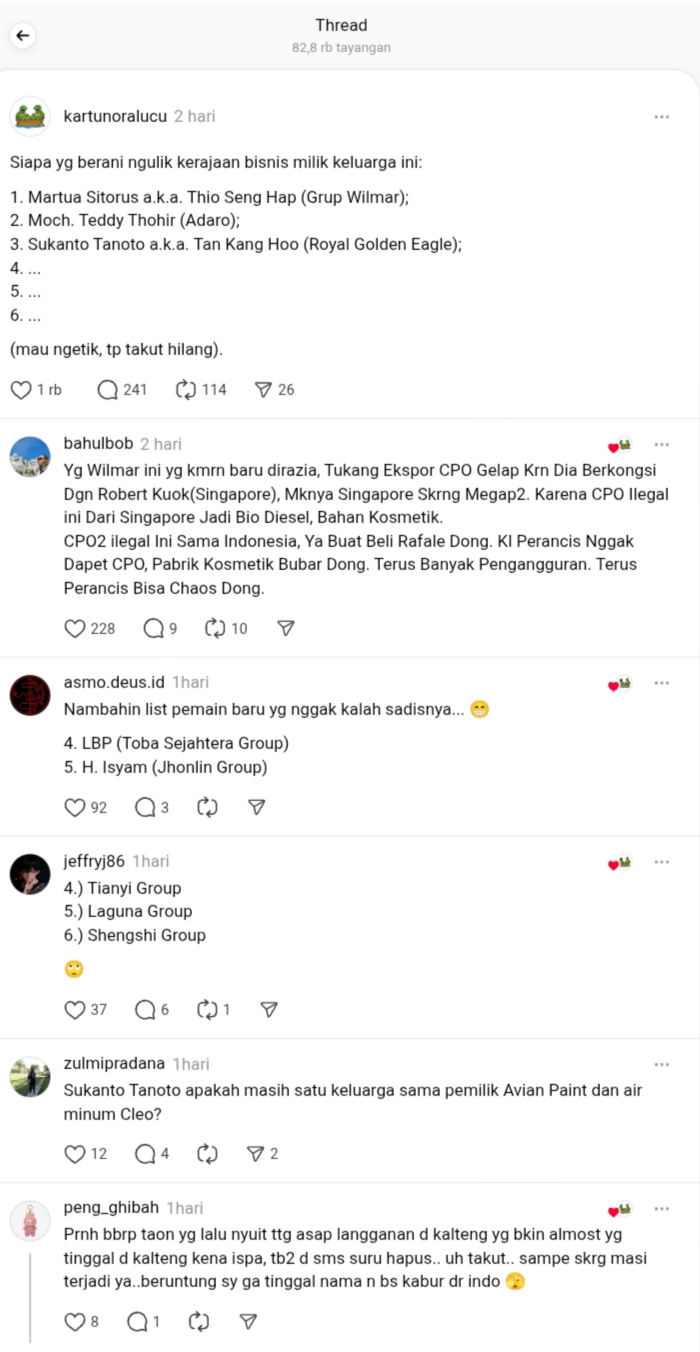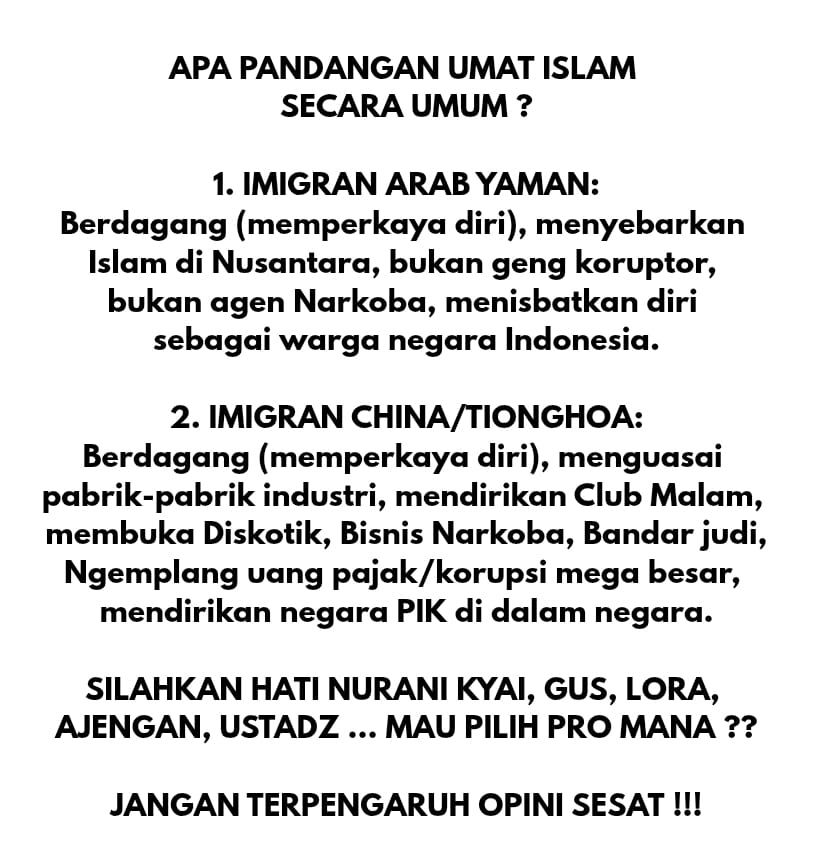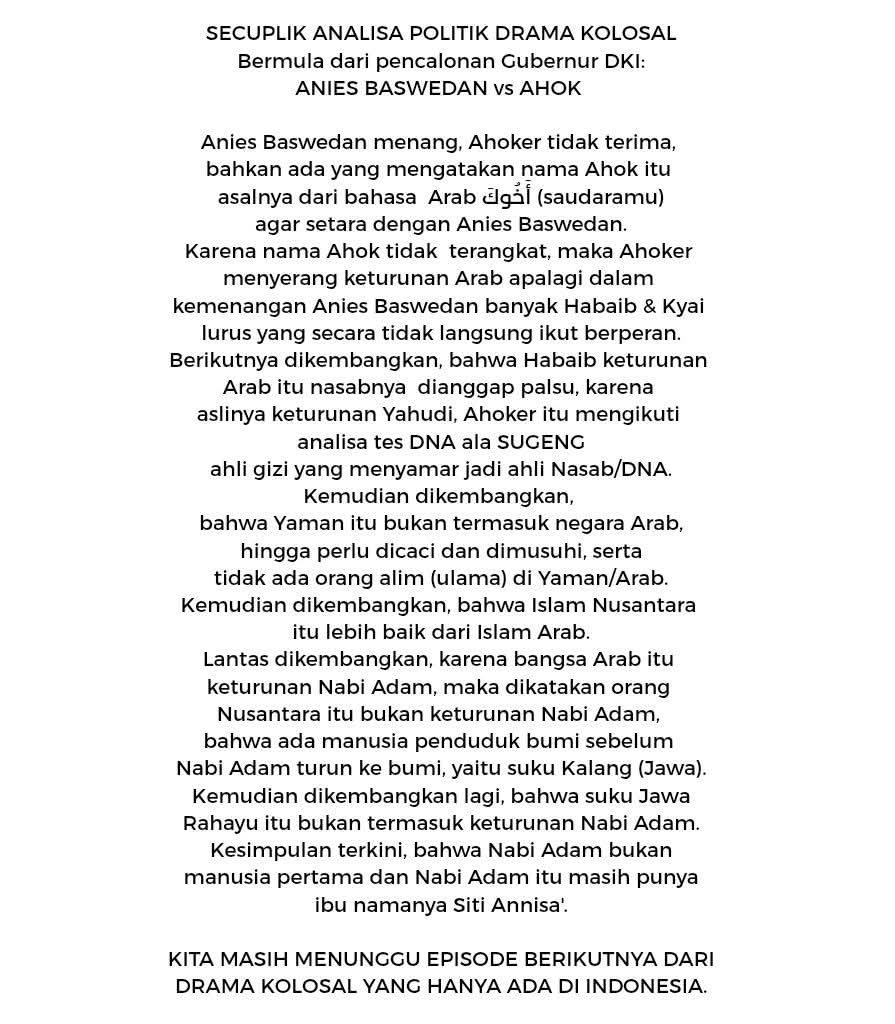✍️ Kang Irvan Noviandana
Bukan rahasia lagi, dunia travel haji dan umrah sudah lama dihantui praktik “pasar gelap” kuota. Sebelum kasus kuota haji reguler dan khusus mencuat ke permukaan, ada jalur yang selama ini jadi ruang bermain para pengusaha travel, visa haji furoda.
Visa furoda sejatinya adalah undangan resmi dari Kerajaan Saudi, di luar kuota nasional Indonesia. Artinya bukan bagian dari sistem antrean resmi pemerintah. Tapi di tangan para pemain travel, visa ini berubah menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Jumlahnya yang terbatas membuat para travel bersaing, bahkan saling menawar dengan harga tinggi. Di lapangan, visa furoda seolah dilelang, siapa berani bayar lebih, dialah yang dapat.
Harga resminya di Saudi tidak sebesar yang akhirnya ditawarkan ke jamaah Indonesia. Di titik inilah praktik tidak sehat muncul, selisih harga disulap menjadi ruang keuntungan besar. Jamaah yang mampu bayar mahal bisa langsung berangkat, sementara jamaah reguler tetap menunggu puluhan tahun. Ironisnya, ibadah yang seharusnya setara di hadapan Allah, justru dipasangi “kelas sosial” di hadapan manusia.
Kini, pola yang sama terbawa masuk ke dalam sistem resmi negara. Kuota tambahan haji yang menurut undang-undang harus didistribusikan mayoritas untuk jamaah reguler, justru dibelokkan ke jalur haji khusus. Mekanismenya tidak jauh berbeda dengan furoda, kuota berubah menjadi barang dagangan, bukan amanah. Hasilnya, ribuan jamaah reguler yang sudah menunggu belasan tahun tersingkir, digantikan mereka yang sanggup membeli jalan pintas.
Inilah pasar gelap praktik bisnis kotor di dunia haji. Pertama, luka bagi jamaah reguler yang haknya dirampas. Kedua, luka bagi umat yang menyaksikan ibadah suci diperlakukan sebagai komoditas dengan nilai tawar. Jika pola ini dibiarkan, maka haji akan semakin kehilangan wajah egaliternya dan hanya menjadi pasar bagi segelintir orang yang berduit.
Korupsi kuota haji bukanlah kasus tunggal. Kasus ini adalah puncak gunung es dari tradisi menyimpang yang sudah lama dibiarkan, menjadikan ibadah sebagai ruang dagang. Maka, kritik terhadap kasus kuota ini seharusnya tidak berhenti pada siapa yang bersalah secara hukum, tapi juga menyentuh akar budaya bisnis yang membelokkan niat ibadah menjadi angka transaksi.